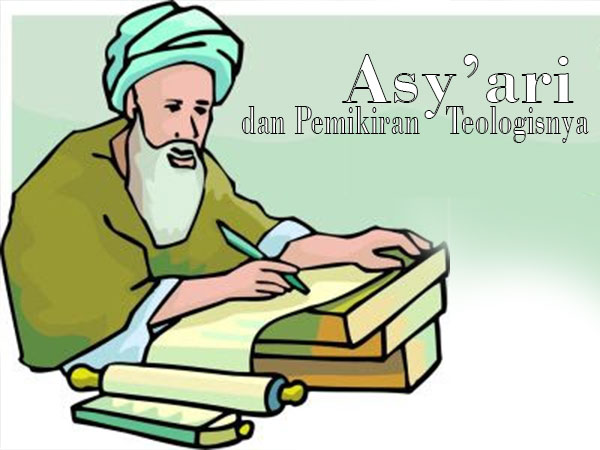
I. Pendahuluan
Paruh kedua abad ketiga merupakan fase penting bagi perkembangan pemikiran di dunia Islam. Masa itu diwarnai kebebasan berpikir setelah beberapa dekade sebelumnya umat Islam hidup di bawah pemerintahan represif yang menjadikan paham Mu’tazilah sebagai teologi resmi pemerintah. Tiap orang bebas menyampaikan pendapatnya tanpa merasa takut akan mendapatkan tekanan dari penguasa.
Iklim yang kondusif bagi perkembangan pemikiran Islam ini bermula ketika al-Mutawakkil yang berkuasa dari tahun 234-247 H. menghapus teologi Mu’tazilah sebagai teologi resmi penguasa dan memberikan keleluasaan bagi aliran lain, khususnya Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Isu Al-Qur`an sebagai makhluk yang banyak menjebloskan ulama non Mu’tazilah ke penjara dicabut dari peraturan pemerintah.
Pada masa itu muncul kelompok-kelompok yang membela pendapat Ahlussunnah dengan menggunakan argumentasi rasional. Tersebutlah nama Abu Hasan al-Asy’ari di Bashroh yang menyatakan dukungannya kepada Ahlussunnah. Dengan metodologi rasional ia membangun teolginya, yang kemudian dikenal sebagai teologi Aswaja.
II. Asy’ari Dan Perkenalannya Dengan Mazhab Mu’tazilah
Ia bernama Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asyari. Asy’ari dilahirkan di Bashroh pada tahun 260 H. dari keluarga terpandang. Sebab, disamping keturunan Arab, jalur nasabnya juga sampai kepada seorang Sahabat Rasulullah, yaitu Abu Musa Al-Asy’ari. Keluarga Asy’ari diyakini sebagai penganut ajaran sunnah. Sebab orang tua Asy’ari pernah berwasiat agar anaknya diserahkan kepada as-Sāji, seorang ulama fikih yang menganut ajaran sunnah, untuk berguru. Asy’ari meninggal pada tahun 324.
Perkenalan intelektualnya dengan mazhab mu’tazilah sudah dimulainya sejak belia. Asy’ary berguru kepada seorang tokoh Mu’tazilah Bashroh, Abu Ali al-Jubbā’ī, hingga mendapatkan posisi terhormat di kalangan penganut Mu’tazilah. Tidak jarang Asy’ari menggantikan gurunya dalam berdebat. Selama berada pada fase kemuktazilahan, Asy’ari menulis beberapa karya yang mendukung serta mempropagandakan mazhab Mu’tazilah.
Setelah menganut Mu’tazilah hingga usia 40 tahun, suatu hari Asy’ari mengasingkan diri di rumahnya selama 15 hari, kemudian keluar menuju masjid dan berkhotbah di atas mimbar. Ada dua versi khotbah Asy’ari. Yang pertama diceritakan Ibnu Khalkan sebagai berikut:
Siapa yang mengenalku, maka ia telah mengenalku. Dan siapa yang tidak mengenalku, maka aku perkenalkan diriku. Aku adalah fulan bin fulan. Dulu aku mengatakan bahwa al-Qur`an adalah mahluk, bahwa Allah tidak dapat dilihat, bahwa manusia menciptakan perbuatan buruknya sendiri. Kini aku bertaubat dari kemu’tazilahan dan meyakini perlunya membantah serta membeberkan kebusukan-kebusukan Mu’tazilah[1] .
Yang kedua diceritakan as-Subkī sebagai berikut:
Wahai orang-orang! Aku menghilang selama ini untuk berpikir dan menimbang dalil-dalil. Tetapi tidak kutemukan satu dalilpun yang lebih kuat dari dalil lain, hingga aku meminta petunjuk Allah. Dan Allah memberiku petunjuk kepada suatu keyakinan yang aku tuliskan dalam buku-buku ini. Aku telah melepaskan diri dari segala keyakinan yang aku yakini selama ini sebagaimana aku melepas bajuku ini.
Di akhir khotbahnya Asy’ary melepas bajunya dan melemparnya. Kemudian ia menyerahkan buku-buku yang ia tulis sesuai aliran ulama fikih dan hadis kepada orang-orang yang hadir[2] .
Tentang alasan keluarnya Asy’ari dari Mu’tazilah, as-Subkī menyebutkan bahwa Asy’ari keluar dari Mu’tazilah setelah bermimpi bertemu Rasulullah Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam. Dalam mimpinya Rasulullah memerintahkan agar Asy’ari membela ajaran Rasulullah dengan ilmu kalam[3]. Tetapi bisa jadi ada alasan lain yang mendorong Asy’ari keluar dari Mu’tazilah. As-Subkī menceritakan sebuah dialog terkenal antara Asy’ary dan gurunya, Ali al-Jubba`ī, sebagai berikut:
Asy’ari : Bagaimana pendapat Guru tentang tiga orang: seorang mu’min, seorang kafir dan seorang anak kecil?
al-Jubba`ī : Yang mu’min mendapatkan yang terbaik, yang kafir masuk neraka, dan yang kecil selamat dari neraka
Asy’ari : Kalau yang kecil ingin mendapatkan tempat yang lebih baik di surga, mungkinkah?
al-Jubba`ī : Tidak. Dan dikatakan kepadanya, “Si Mu’min mendapatkan tingkatan ini karena ketaatannya. Sedangkan kamu (anak kecil) tidak memiliki ketaatan itu”.
Asy’ari : Kalau anak kecil itu berkata, “Itu bukan salahku. Sekiranya Engkau bolehkan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Si Mu’min itu”?
al-Jubba`ī : Allah akan menjawab, “Aku tahu, jika engkau terus hidup, engkau akan berbuat maksiat dan engkau akan mendapat siksa. Maka, Aku lindungi kepentinganmu dengan mematikanmu sebelum mencapai usia baligh”
Asy’ari : Sekira si kafir mengatakan, “Ya Tuhanku, Engkau ketahui masa depanku sebagaimana Engkau ketahui masa depannya. Mengapa tidak engkau lindungi kepentinganku?”
al-Jubba`ī : !!! (hanya terdiam)[4]
Di atas telah disinggung bahwa dalam pengasingannya Asy’ari tidak menemukan pendapat yang benar hinnga akhirnya ia mendapat petunjuk Allah. Artinya, Asy’ari sempat mengalami situasi dimana ia meragukan semua pendapat-pendapat teologis yang ada. Dan dialog di atas sangat mungkin merupakan wujud keraguan Asy’ari terhadap teologi Mu’tazilah. Dalam keraguan itulah Asya’ri melakukan perenungan selama 15 hari, hingga akhirnya mendapat petunjuk Allah tentang mana pendapat teologis yang benar. Dengan demikian alasan keluarnya Asy’ari mulanya didorong oleh ketidakpuasan dan keraguan yang bersifat rasional dan berakhir dengan ditemukannya keyakinan tentang teologi yang benar melalui mimpi.
III. Kondisi Politik dan Ekonomi
Asy’ari hidup diantara awal paruh kedua abad 3 Hijriyah dan seperempat pertama abad 4 Hijriyah. Ia mengalami masa tujuh pemerintahan, yaitu pemerintahan Al-Mu’tamid, Al-Mu’tahid, Al-Muktafi Billah, Al-Muqtadir Billah, Al-Qohir dan Ar-Rodli Billah. Masa itu adalah masa yang penuh dengan pergolakan politik. Perebutan kekuasaan di kalangan keluarga dari satu sisi, dan perebutan pengaruh di kalangan pembantu raja di sisi lain merupakan pemandangan yang selalu mewarnai kepemimpinan raja-raja Abasiyah. Hampir setiap pergantian kepemimpinan diwarnai dengan pertumpahan darah.
Di daerah-daerah banyak terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan Abbasiyah di pusat. Di Timur, tentara Turki menguasai Irak. Di Barat, koalisi pasukan Arab, Barbar, dan Zinji menguasai Qaeruwan, Tahrat dan Fas. Pada awal abad 4 muncul tiga kekuatan yang mampu menggulingkan kekuatan Abbasiayah di beberapa daerah, masing-masing adalah kerajaan Bani Buwaih di Irak, kerajaan Hamdaniyun di Syiria, dan kerajaan Fatimiyah di Mesir.
Rapuhnya pemerintahan Abbasiyah dibarengi dengan berkuasanya kekuatan luar atas daerah-daerah perdagangan internasional dan tergusurnya peran dunia Islam sebagai perantara perdagangan timur dan barat. Berkuasanya perdagangan Cina di timur telah menumbangkan dominasi perdagangan Islam di laut India. Para pedagang Muslim diusir dari pusat-pusat perdagangan di Cina. Hal itu terjadi setelah pemerintahan Cina yang pro Islam digantikan oleh pemerintahan baru yang anti Islam. Di Asia Barat naiknya kekuatan militer Macedonia ke tampuk pimpinan Konstantinopel mengakibatkan terusirnya orang Islam dari daerah yang didudukinya di Asia Kecil. Kekuasaan Konstantinopel terus meluas sampai ke daerah Irak atas, Syam, Armenia, serta berhasil merebut kembali Cyprus dan menguasai pelayaran di laut tengah bagian timur.
Munculnya Cina di Asia timur dan Konstantinopel di Asia Barat telah memutus jalur perdagangan dunia Islam Timur dan Dunia Islam Barat, serta mengakhiri peran pedagang muslim sebagai perantara perdagangan Asia dan Eropa.
Berkuasanya pasukan Arab Badui dan non arab yang feodalistis di daerah daerah, dan berakhirnya peran pedagang muslim sebagai perantara perdagangan Asia dan Eropa mengakhiri masa borjuisme dan kembali ke masa feodalisme. Dengan demikian Asy’ari hidup pada masa feodalisme baru.
IV. Karya-Karya Asy’ari
Selama pengembaraan intelektualnya, Asy’ari telah banyak mengahsilkan karangan. Ibnu ‘Asākir mencatatat daftar panjang buku karangan Asy’ari dan kebanyakan merupakan bantahan Asy’ari terhadap teologi sekte lain dalam Islam maupun teologi agama lain. Dari sekian buku tercatat ada empat yang terkenal, yaitu:
- Al-Ibānah ‘An Uṣul al-Diyānah. Dalam buku ini Asy’ari condong dan menyatakan diri mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal
- Al-Luma’ fi al-Rodd ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bida’. Buku ini merupakan pengejawantahan kecenderungan rasional Asy’ari dan implementasi dari moderasi ekstrem rasio dan teks.
- Maqālat al-Islāmiyyin. Buku yang ditulis secara obyektif dan jujur ini mengetengahkan pendapat-pendapat teologis sekte-sekte agama.
- Istihsān al-Khauḍ Fi ‘Ilm al-Kalām. Sebuah buku yang membela ilmu kalam dari serangan kelompok yang anti ilmu kalam. Buku ini juga mencerminkan kecenderungan rasional Asy’ari
IV. Hegemoni Mu’tazilah Selama Tiga Periode Kepemimpinan
Selama masa kepemimpinan al-Ma’mun, al-Watsiq dan al-Mu’tashim paham Mu’tazilah menjadi ideologi resmi negara. Para khalifah itu mengeluarkan kebijakan yang sering disebut dengan mihnah mahkluqiyatul al-Qur`an[5]. Ibnu al-Atsir dalam al-Kamil fi at-Tarikh menceritakan:
Di tahun ini (218 H.) al-Ma’mun mengeluarkan dekrit yang memerintahkan Ishaq bin Ibrahim agar menguji keyakinan para hakim, saksi dan ahli hadis tentang Al-Qur`an. Siapa yang meyakini bahwa Quran adalah makhluk maka ia akan dibebaskan. Dan siapa yang menolak keyakinan itu, maka ia harus diberitahu bahwa khalifah al-Ma’mun memerintahkan hal tersebut. Di dalam dekritnya al-Ma’mun berbicara panjang lebar tentang kemakhlukan Al-Qur`an dan mengajukan berbagai argumentasi yang mendukungnya. al-Ma’mun juga mengatakan bahwa ia tidak akan menggunakan jasa orang-orang yang anti terhadap kemakhlukan al-Quran. Dekrit ini ditulis pada bulan Rabi’ul Awal dan untuk pertama kalinya diberlakukan kepada tujuh ulama yaitu: Muhammad bin Sa’ad, Abu Muslim Yazid bin Harun, Yahya bin Ma’īn, Abu Khaithamah Zuhair bin Harb, Ismail bin Daud, Ismail bin Abi Daud dan Ahmad bin ad-Dawraqī. Ketujuh orang inipun ditanya keyakinannya tentang Al-Qur`an. Mereka semua menjawab bahwa Al-Qur`an adalah Makhluk[6].
Dari penuturan di atas dapat dilihat bahwa al-Ma’mun sebagai khalifah telah menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan paham Mu’tazilah sebagai ideologi negara. Al-Ma’mun memang dikenal khalifah yang ulama. Dan sejak awal al-Ma’mun memang meyakini bahwa paham Mu’tazilah-lah yang benar. Hal itu dapat dilihat dari dekrit al-Ma’mun yang juga disertai argumentasi tentang kebenaran kemakhlukan Al-Qur`an.
Sebenarnya dekrit serupa sudah pernah dikeluarkan al-Ma’mun pada tahun 212. Bahkan dalam dekrit tahun 212 juga disebutkan tentang kewajiban mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas Abu Bakar dan Umar. Tetapi dekrit ini dicabut karena mempertimbangkan kemungkinan terjadinya situasi yang tidak menguntungkan al-Ma’mun. Baru pada tahun 218 al-Ma’mun mengeluarkan dekrit itu melalui gubenur Baghdad saat itu, Ishaq bin Ibrahim[7].
Jadi, pada masa al-Ma’mun paham Mu’tazilah mendapatkan ruang yang luas untuk mengembangkan dan memperluas pengaruhnya.
Kebijakan “kemakhlukan Al-Qur`an” dilanjutkan al-Mu’tashim yang bertahta dari tahun 218 hingga tahun 227[8]. Lebih jauh al-Mu’tashim menjadikan kemahklukan Al-Qur`an sebagai kurikulum wajib yang harus didoktrinkan kepada para pelajar. Demikian pula ketika al-Wathīq berkuasa dari tahun 227 sampai dengan 232, kemakhlukan Al-Qur`an masih menjadi kebijakan pemerintah. Dan ketika menebus tawanan perang dari Romawi, atas saran Ahmad bin Abi Duad, al-Watsiq mengeluarkan kebijakan yang diskrimatif, yaitu siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah Makhluk, maka ia ditebus dan diberi hadiah 2 dinar dan siapa yang membangkang, maka ia dibiarkan tetap ditawan. Tetapi di akhir hayatnya al-Watsiq mencabut kebijakan “kemakhlukan Al-Qur`an”[9].
Jadi, selama kurun waktu antara tahuan 218 hingga 232, atau selama 14 tahun, sebuah hegemoni politik telah mengabsolutkan kebenaran paham Mu’tazilah dan berusaha memberangus paham-paham lain, khusunya paham ahli hadis dan ahli fikih yang dianut mayoritas umat saat itu.
Tetapi keadaan berbalik 180 derajat ketika al-Mutawakkil berkuasa. Pada tahun 234 al-Mutawakkil mencabut kebijakan “Kemakhlukan Al-Qur`an”. Lebih jauh Al-Mutawakkil mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontra Mu’tazilah. Diantara kebijakan itu adalah mendatangkan para ahli hadis untuk menyebarkan ajaran tentang sifat-sifat Allah dan bahwa Allah akan dilihat orang mu’min di akhirat kelak. Al-Mutawakkil juga mencopot seorang hakim di Mesir yang dianggap berpaham Jahamiyah[10]. Tidak seperti para pendahulunya yang melakukan berbagai siksaan terhadap Ahmad bin Hanbal atas pembangkangannya, al-Mutawakkil, justru sebaliknya, memberikan perlakuan istimewa kepadanya[11].
Dari Mu’tazilah sentris, kekahalifahan Abbasiyah saat itu berbalik menjadi Ahmad bin Hanbal Sentris. Perubahan ini tentu mempengaruhi konstelasi pertarungan antar pemikiran. Represi berlebihan yang diterima Ahmad bin Hanbal dan koleganya memunculkan reaksi serupa dari para pengikut Ahmad bin Hanbal. Perlawanan terhadap paham Mu’tazilah menjadi lebih keras dibanding sebelumnya. Perlawanan keras ini juga mewujud dalam bentuk pengembangan teologi pengikut sunnah yang pada perkembangannya melahirkan pendapat ekstrem tentang tafwiḍ yang tidak lagi berjarak dengan paham mujassimah dan musyabbihah. Tak pelak tafwiḍ ekstrem ini memunculkan mujassimah baru dan memberikan angin segar bagi mujassimah lama yang dipelopori oleh Syiah Imamiyah untuk kembali tampil di permukaan.
Kini di panggung pemikiran teologi Islam tampil dua arus utama yang saling berlawanan: Mu’tazilah dengan berbagai variannya yang rasionalis dan pengikut Ahmad bin Hanbal dengan berbagai variannya yang tekstualis. Dalam situasi seperti ini munculnya sintesa dari kedua kutub ekstrem menjadi sebuah keniscayaan. Lahirlah paham baru yang memoderasi ekstrem teks dan rasio. Di Irak paham moderat ini dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy’ari, di Mesir oleh ath-Thahāwī dan di Samarkand oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Di tangan al-Asyari, paham Mu’tazilah akhirnya menepi dari pergulatan pemikiran teologi Islam.
V. Tema sentral Teologi
Pada masa Sahabat tidak ada yang mempersoalkan bahwa Al-Qur`an adalah kalam Ilahi dan bukan makhluk. Kemudian muncul Jahm bin Shofwan pada masa tabi’in yang mengemukakan gagasan baru bahwa Al-Qur`an adalah makhluk. Tetapi pengaruh Jahm bin Shofwan tidak bertahan lama. Baru setelah Mu’tazilah mengangkat kembali isu ini dengan dukungan argumentasi rasional dan kekuasaan politik, perdebatan tentang kemahklukan al-Qu’ran menjadi tema sentral di panggung pemikiran teologi Islam. Oleh karena itu memahami tema sentral yang berkembang di masa al-Asyari harus dirunut dari kemunculan Mu’tazilah. Sebab Mu’tazilah-lah yang mula-mula memunculkan isu-isu tersebut sebelum kemudian direspon oleh Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya.
Di dalam Mu’tazilah terdapat ajaran tentang lima pokok keimanan yaitu, al-Tawhīd, al-Adl, al-Wa`d wa al-Wa’īd, al-Manzilah bayn al-Manzilatayn, al-Amr bi al-Ma`rūf wa an-Nahyu `an al-Munkar. Seluruh aliran Mu’tazilah dengan berbgai variannya mengakui lima pokok keimanan ini. Dari kelima pokok keimanan ini, al-Tawhid dan al-Adl menurunkan berbagai gagasan kontroversial yang muncul dari penjabaran logis atas kedua ajaran tersebut.
Al-Tawhid dipahami Mu’tazilah sebagai pengesaan yang utuh terhadap Tuhan. Tuhan maha esa, tidak ada yang menyerupaiNya, bukan benda, bukan materi tak terbagi, tidak bertempat, tidak bersuhu, tidak berkelembaban, tidak tdisebut bergerak juga tidak diam, tidak berdimensi, tidak memiliki kekurangan ataupun cela. Tuhan tidak seperti apapun yang tergambar dalam halusianasi manusia[12].
Keimanan ini menurunkan gagasan nafy al-ṣifāt (meniadakan sifat-sifat Tuhan). Nafy al-ṣifāt pertama kali digagas oleh pendiri Mu’tazilah Washil bin Atho`. Menurutnya, tidak mungkin ada dua tuhan yang qadīm[13]. Dan menetapkan sifat-sifat kepada Tuhan sama dengan menetapkan qadīm-qadīm lain selain Tuhan[14]. Demikian pun al-Al-Qur`an tidak mungkin bersifat qadīm. Sebab jika demikan, Al-Qur`an akan menjadi qadīm-qadīm yang lain selain Tuhan. Dan karenanya Mu’tazilah berpendapat bahwa Al-Qur`an adalah makhluk. Konsekwensi logis dari ajaran tersebut di atas adalah bahwa setiap ayat yang sekilas mengesankan adanya sifat-sifat yang mencedarai keesaan Tuhan harus ditafsirkan lain atau disebut ta’wīl.
Gagasan lain yang diturunkan dari doktrin keimanan al-tawhid adalah nafy al ru’yah, yaitu bahwa Tuhan tidak dapat dilihat. Menurut Mu’tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat. Sebab, jika Tuhan bisa dilihat berarti Tuhan berhadap-hadapan dengan orang yang melihat. Dan itu artinya Tuhan memerlukan tempat. Padahal seperti telah dikemukakan di muka, Tuhan tidak memerlukan tempat. Sebab yang bertempat hanyalah materi. Oleh karena itu mengatakan bahwa Tuhan bisa dilihat sama dengan mengatakan Tuhan adalah benda atau materi, dan itu sama dengan mencederai keesaan Tuhan.
Sedangkan al-Adl, menurut Mu’tazilah adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan kearifan akal, yaitu perbuatan yang baik dan bermanfaat untuk makhlukNya. Jika Tuhan tidak berbuat selain untuk kebaikan dan kemanfaatan makhlukNya, hal itu berarti bahwa Tuhan wajib menjaga kepentingan hambaNya[15]. Dalam diskursus teologi, kewajiban Tuhan in idikenal dengan istilah al-Ṣalāḥ wa al-Aṣlaḥ atau yang baik dan terbaik.
Konsekwensi logis dari ajaran tersebut adalah bahwa manusia harus memiliki kebebasan dalam memilih antara yang baik dan buruk. Sebab, jika kehendak buruk manusia disematkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bersifat buruk. Sebab dalam logika Mu’tazilah, menghendaki keburukan adalah keburukan. Dan seperti telah disebutkan di muka, berdasarkan doktrin al-Adl, Tuhan tidak mungkin bersifat buruk. Disamping memiliki kebebasannya, menurut Mu’tazilah manusia juga menciptakan perbuatan buruknya sendiri. Sebab, seperti disebutkan di atas, Tuhan hanya menghendaki kebaikan. Jika perbuatan buruk manusia diciptakan Tuhan, berarti Tuhan melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Dan melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya adalah sebuah ketololan atau keterpaksaan yang tidak mungkin terjadi pada Tuhan. Tema tentang kebebasan berkehendak ini dikenal dengan istilah qadlā’ dan qadar.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa tema teologis yang dimunculkan oleh Mu’tazilah, yaitu: nafy al-ṣifāt, nafy al-ru’yah, ta’wil, al-Ṣalāḥ wa al-Aṣhlaḥ serta qadlā’ dan qadar. Sebenarnya masih banyak gagasan lain Mu’tazilah yang menyulut kontroversi. Tetapi lima tema inilah yang terpenting dan kelak mempengaruhi mazhab teologi Al-Asyari.
VI. Pokok-Pokok Pemikiran Asy’ary
Bagi para pengikutnya, Asy’ari adalah imam yang pendapatnya diikuti dan dijadikan rujukan. Dengan kata lain, pendapat Asy’arian sesuai dengan kaidah-kaidah teologis Asy’ari. Tetapi tidak demikian bagi sebagian pengikut Ibnu Taimiyah, yang kemudian diwarisi oleh Wahabi. Bagi mereka pendapat dan metodologi Asy’ari sesuai dengan pendapat dan metodologi Ahmad bin Hanbal. Dan para Asy’arian telah melenceng dari ajaran imamnya, Asy’ari. Klaim sebagian Wahabi didasarkan pada kitab al-Ibānah yang banyak memuji Ahmad bin Hanbal dan sering menggunakan metode tafwīḍ. Menurut mereka al-Ibānah adalah fase terakhir pemikiran Asy’ari[16]. Karena itu bagi sebagian Wahabi, Asy’ari disebut telah bertaubat dan kembali ke jalan Ahmad bin Hanbal setelah sebelumnya menganut mazhab ta’wīl, seperti yang dilakukan kebanyakan Asy’arian.
Disamping mengaku sebagai pengikut mazhab Salaf dan memuji-muji Ahmad Bin Hanbal, dalam al-Ibānah Asy’ari juga mengkritik mazhab Mu’tazilah dan mazhab lain yang dianggap sesat. Mu’tazilah telah melakukan ta’wīl tanpa menggunakan dasar dari Al-Qur`an, sunnah Rasulullah Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam ataupun dari pendapat ulama terdahulu. Mu’tazilah juga menentang riwayat para sahabat yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Allah akan dilihat orang mu’min di surga kelak. Mereka telah mengagamakan “kemahklukan al-Quran”, sama dengan pendapat orang-orang musyrik sebagaimana dikisahkan Al-Qur`an:
إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ
Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. (QS,74:25)
Di dunia ini akan banyak tuhan-tuhan yang menjadi pesaing Tuhan dalam mencipta. Sebab menurut Mu’tazilah manusia menciptakan perbuatan buruknya sendiri. Mu’tazilah telah menciderai kesempurnaan Tuhan ketika mengatakan bahwa manusia memiliki kehendaknya sendiri yang terlepas dari kehendak Tuhan. Berarti menurut Mu’tazilah di dunia terdapat sesuatu yang ada bukan karena kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan Mu’tazilah sama dengan pendapat kaum Majusi yang mengatakan, terdapat dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Bahkan pendapat Mu’tazilah lebih buruk, karena bagi majusi hanya ada dua Tuhan, sedangkan Mu’tzilah mengakui banyak tuhan. Karena itulah Rasulullah Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam menyebut qadariyah sebagai majusinya umat Islam. Pendeknya Mu’tazilah secara tidak langsung telah menolak Al-Qur`an dan sunnah Rasulullah Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam, menentang ijma’ para sahabat dan ulama terdahulu[17].
Dari uraian di atas dapat dilihat bagaimana pada fase al-Ibānah Asy’ari menghujat keras kelompok di mana dulu ia pernah berafiliasi, yaitu kelompok Mu’tazilah. Hal semacam ini biasanya terjadi di saat seseorang keluar dari suatu mazhab karena ketidakcocokannya. Dalam situasi seperti ini biasanya orang akan terjebak pada ekstrem yang bersebarangan.
Di dalam al-Ibanah Asy’ari tidak mengemukakan gagasan baru. Apa yang disebutnya sebagai aqidah yang benar adalah keyakinan-keyakinan para ulama terdahulu yang selama ini menjadi mainstream pemikiran teologi Islam.
Di sisi lain dalam Istihsān al-Khawḍ, Asy’ari jelas bersemangat menggunakan metode ta’wīl dan pendekatan ilmu kalam dalam pembahasan teologi. Bahkan Asy’ari mengkritik orang-orang yang anti ta’wīl dan ilmu kalam. Dalam Istihsān Asy’ari berkata:
Sekelompok orang telah menjadikan kebodohan sebagai modalnya. Mereka merasa berat untuk berpikir dan berbicara tentang agama. Ada kecenderungan pada diri mereka untuk memilih pekerjaan yang ringan dan taqlid. Mereka mencela orang-orang yang melakukan penelitian tentang aqidah dan menyebutnya sesat. Bagi mereka membicarakan gerak, diam, benda, sifat benda, warna, ke-ada-an, lompatan[18] , dan sifat-sifat Tuhan adalah bid’ah dan kesesatan. Mereka berdalih, kalau membicarakan hal tersebut adalah kebenaran, tentu Rasulullah Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam, demikian pula para sahabatnya, sudah membicarakannya. Sebab Rasulullah Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam tidak akan meninggal sebelum menjelaskan seluruh persoalan agama yang dibutuhkan umatnya. Faktanya Rasulullah Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam tidak mewasiatkan kepada seorangpun agar berbicara mengenai persoalan-persoalan agama yang dibutuhkan umat dan hal –hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah ataupun menjauhkan diri dari siksa Allah. Karena tidak ditemukan satu riwayatpun dari Rasulullah Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam yang membicarakan hal-hal tersebut, berarti membahasnya adalah bid’ah dan kesesatan…[19]
Dalam kutipan tersebut, Asy’ari mengkritik kaum tekstualis yang mengkritik ilmu kalam. Bahkan dengan nada mengecam, Asy’ari menyebut mereka sebagai pemalas yang tidak mau bersusah payah memikirkan hal rumit.
Seperti diketahui bahwa dalam al-Ibānah Asy’ari mengecam keras ta’wīl yang dilakukan Mu’tazilah. Tetapi dalam Istihsān Asy’ari justru menolak pemahaman tekstualis. Apakah dengan demikian Asy’ari telah berbalik menjadi Mu’tazilah?
Pada dasarnya Asy’ari tidak menggagas substansi baru yang bertentangan dengan keyakinan para ulama salaf. Asy’ari berpendapat bahwa al-Qur`an adalah kalam Ilahi yang qadīm; Tuhan akan dilihat orang mu’min di surga kelak; semua hal baik dan buruk yang terjadi di dunia ini adalah ciptaan dan atas kehendak Tuhan; Tuhan memiliki sifat ḥayāt, qudrah, irādah, “ilmu, sama’, kalām. Disamping itu Asy’ari, tidak seperti ulama salaf, juga memberikan ruang bagi akal untuk menjelaskan dan membicarakan keyakinan-keyakinan tersebut secara rasional. Pola pendekatan Asy’ari semacam inilah yang kemudian berimplikasi pada terjadinya benturan-benturan dengan para pengikut Ahmad bin Hanbal yang menyatakan diri sebagai penerus teologi ulama salaf.
Namun demikian Asy’ari membatasi diri untuk tidak membiarkan akal melampaui ketentuan teks al-Qur`an maupun Hadis ataupun Ijma’ Sahabat, sebagaimana pola pendekatan rasional Mu’tazilah yang ia kritik. Jika ketentuan teks dianggap qoṭī, maka Asy’ari tidak melakukan ta’wīl. Pada titik inilah, kadang Asy’ari terjebak pada argumentasi-argumentasi yang sulit diterima.
Berikut beberapa contoh pola pendekatan rasional Asy’ari dalam membahas teologi.
A. Kalam Ilahi
Seperti telah disebut di atas Asy’ari meyakini bahwa bahwa al-Al-Qur`an adalah kalam Ilahi yang bersifat qādim. Untuk mendukung pendapatnya, Asy’ari mengajukan argumentasi rasional, disamping tentunya juga mengajukan argumen tekstual. Allah Berfirman:
إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami Hanya mengatakan kepadanya: kun (jadilah), Maka jadilah ia. (QS, 16:40)
Pengertian “sesuatu” pada ayat di atas bersifat umum, yang berarti mencakup juga al-Al-Qur`an yang menurut mu’tazilah adalah makhluk. Berarti Al-Qur`an dalam pengertian Mu’tazilah juga diciptakan dengan kalimat “jadilah”. Pada saat yang sama Mu’tazilah juga mengakui bahwa Al-Qur`an adalah kalam Ilahi tetapi bersifat ḥadīs[20]. Jika demikian, maka mustahil Allah menciptakan kalamNya dengan kalimat “jadilah”. Sebab kalimat “jadilah” juga kalam Allah yang berarti harus diciptakan dengan kalimat “jadilah” lain, dan begitu seterusnya hinnga terjadi mata rantai “jadilah” yang tak berujung. Dengan demikian tidak mungkin Al-Qur`an diciptakan dengan kalimat “jadilah” seperti ciptaan-ciptaan lain. Dan jika Al-Qur`an tidak mungkin diciptkan dengan kalimat “jadilah”, berarti Al-Qur`an tidak bersifat ḥadīs. Dan jika Al-Qur`an tidak bersifat ḥadīs , maka pastilah Al-Qur`an bersifat qadīm[21].
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah yang qadīm pada Al-Qur`an? Lafadz dan maknanya-kah? Atau hanya maknanya saja? Asy’ari berpendapat bahwa kalām adalah sesuatu yang bertempat pada diri mutakallim (قائم بذات المتكلم). Kalām dalam pengertian ini berarti bukan huruf atau suara, melainkan kata yang berada di dalam diri. Kalām ini diistilahkan dengan kalām nafsī[22].
Ada tiga kesimpulan yang bisa ditarik dari uraian diatas. Pertama, bahwa Asy’ari menolak huruf-huruf yang terdapat dalam mushaf disebut kalam Ilahi yang qadīm. Dengan demikian, pendapat Asy’ari tentang kalām berbeda dengan pendapat Hanabilah yang menganggap bahwa huruf-huruf dalam mushaf juga termasuk kalam yang qadīm[23]. Justru sebaliknya, pendapat Asy’ari sama dengan Mu’tazilah yang mengatakan mushaf dengan segala perangkat kerasnya bersifat ḥadīs. Perbedaan Asy’ari dan Mu’tazilah terletak pada pengertian kalām nafsī yang disebut Asy’ari sebagai bersifat qadīm.
Kedua, seperti telah disebutkan di atas, pendekatan Rasional Asy’ari dalam mendukung pendapat-pendapat ulama salaf tidak akan terhindar dari benturan-benturan dengan pendapat ulama salaf itu sendiri. Awalnya Asy’ari dapat menjelaskan secara rasional bahwa Al-Qur`an adalah kalam Ilahi yang bersifat qadīm. Tetapi ketika memasuki pembahasan yang lebih detail tentang apakah yang qadīm dari Al-Qur`an, Asy’ari harus berseberangan dengan Hanabilah yang merepresentasikan pendapat ulama salaf. Sebab, mengatakan huruf-huruf dalam mushaf yang bisa dirusak dan dibakar sebagai bersifat qadīm adalah hal yang konyol dan sama sekali tidak rasional.
Ketiga, Asy’ari telah memunculkankan terminologi baru yang disebut dengan kalām nafsī. Istilah ini dimunculkan untuk menjembatani kerumitan-kerumitan terkait dengan hal-hal yang jelas-jelas bersifat ḥadīs dan kalam Ilahi itu sendiri yang dipastikan bersifat qadīm.
B. Ru’yatullah
Rasulullah ditanya, apakah kita akan melihat Tuhan kita di hari kiamat. Rasulllah menjawab, “iya” [24]. Berdasarkan hadis ini dan dalil-dalil lain dalam Al-Qur`an dan hadis, ulama salaf berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh orang mu’min kelak di hari kiamat. Bagaimanakah Asy’ari merasionalisasi keyakinan ini? Pertama-tama Asy’ari menjelaskan sebuah prinsip, yang sebenarnya juga menjadi prinsip dari keseluruhan teologinya. Segala sesuatu yang tidak mengakibatkan kebaruan Tuhan, kebaruan sifat yang ada pada Tuhan, kebendaan Tuhan, keserupaan Tuhan dengan makhluk, berubahnya Tuhan dari hakikatNya, kedzaliman Tuhan dan pendustaan kepada Tuhan, maka tidak dihukumi mustahil. Terlihatnya Tuhan tidak mengakibatkan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, terlihatnya Tuhan bukanlah perkara yang mustahil.
Kemudian Asy’ari menjelaskan bahwa terlihatnya Tuhan tidak mengakibatkan kebaruan Tuhan. Sebab kalau yang terlihat itu bisa terlihat karena ia terbarukan, maka seharusnya semua yang terbarukan bisa terlihat. Padahal menurut Mu’tazilah yang menjadi sasaran argumentasi ini, tidak semua yang terbarukan bisa terlihat. Demikian pula, terlihatnya Tuhan tidak akan menimbulkan sifat baru pada Tuhan. Sebab warna, yang merupakan sifat, juga terlihat. Kalau terlihat menimbulkan sifat baru pada sesuatu yang terlihat, maka melihat itulah yang akan menjadi sifat baru[25].
Telah dikemukakan di atas bahwa sepanjang teks-teks Al-Qur`an ataupun Hadis menunjuk pada makna yang pasti, maka tidak ada jalan lain selain mengikuti makna tersebut tanpa ta’wīl. Dalam penjelasannya tentang Ru’yatullah, Asy’ari menambahkan prinsip lain yang intinya, selama sebuah penafsiran tidak mengakibatkan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan Tuhan, maka penafsiran itu dapat digunakan. Dan kedua prinsip ini diterapkan secara berurutan. Jika kedua prinsip tersebut digabungkan dengan prinsip rasionalitas, maka pendekatan teologi Asy’ari dapat dirumuskan sebagai berikut: suatu penafsiran yang rasional terhadap masalah-masalah aqidah dapat dilakukan sepanjang tidak berbenturan dengan teks al-Qur`an ataupun hadis yang qaṭ’ī dan tidak pula mengakibatkan pencideraan terhadap kesempurnaan sifat-sifat Tuhan.
Disamping itu, penjelasan di atas sekali lagi memperlihatkan bagaimana Asy’ari kadang tergelincir dalam menyusun argumentasinya. Mu’tazilah, yang menjadi sasaran penjelasan di atas tidak mengatakan bahwa terbarukan adalah sebab, melainkan syarat dari melihat Tuhan. Sehingga tidaklah benar kesimpulan Asy’ari, “…maka seharusnya semua yang terbarukan bisa terlihat”. Dan pada kasus ini Asy’ari dapat dianggap gagal memberikan penjelasan rasional tentang ru’yatullah[26]. ©tamma bihamdillah, 2012
[1] Syamsuddin Ibnu Kholkān, Wafayāl al- A’yān, (Beirut: Dār Ṣādir, 1994) 3:285.
[2] Tajuddin As-Subky, Tabaqāt al-Shāfi’iyyah al-Kubra, (Cairo: Dār Iḥya’ al-Kutub al-Arabiyyah, tth), 3:347-348.
[3] Ibid, 3:348
[4] Ibid, 3:356
[5] Inti dari kebijakan ini adalah bahwa setiap warga, khususnya para ulama, hakim, dan pejabat pemerintah, harus meyakini bahwa al-Qur`an adalah makhluk dan keyakinan ini merupakan salah satu ajaran Mu’tazilah. Siapapun yang menolak keyakinan tersebut akan mendapat hukuman fisik.
[6] Izzuddin Ibnu al-Athīr, al-Kāmil fi al-Tārīkh, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1997), 5:572.
[7] Jalaluddin al-Suyuthi, Tārīkh al-Khulafā`, (Makkah: Matabah Nizār Mushṭafa al-Bāz, 2004), 227.
[8] Ibid, 224.
[9] Ibid, 249.
[10] Ibid, 252.
[11] Abu al-Fidā` Ismail Ibnu Kathir, al-Bidāyah wa al-Nihāyah, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 10:316.
[12] Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asyari, Maqālāt al-Islāmiyyin wa Ikhtilāf al-Muṣallīn, (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1990), 1:235.
[13] Sesuati=u yang keberadaanya tidak didahului ketiadaan.
[14] Abu al-Fatḥ Muhammad bin Abdul Karim al-Shahrastanī, Al-Milal wa al-Niḥal, (Cairo: Muassasat al-Ḥalabī, tth), 1:46
[15] Ibid, 1:47.
[16]Hamad Sinan dan Fauzi al-Anjari, Ahl al-Sunnah al-Asyā’irah Shahādat ‘Ulamā` al-Ummah wa Adillatuhum, (Kuwait: Dār al-Dliyā’, 2006), 42.
[17] Lihat Abu al-Hasan Al-Asy’ary, Al-Ibānah ‘An Uṣūl al-Diyānah(Cairo: Daar al-Anshor, 1977), 14-19.
[18] Semuanya adalah istilah-istilah di dalam ilmu kalam.
[19] Abu al-Hasan Al-Asy’ari, Istihsān al-Khauḍ fi’Ilm al-Kalām, (Beirut: Dār al-Mashāri’, 1995), 38.
[20] Sesuatu yang keberadaannya didahului ketiadaan.
[21] Abu Hasan al-Asyari, al-Luma` fi al-Radd `Ala Ahl al-Zaygh wa al-Bida’, (Cairo: Shirkat Musāhamah Maṣriyyah, 1955), 33-34. Lihat pula, Abu Hasan al-Asyari, al-Ibānah ‘an Uṣūl al-Diyānah, (Cairo: Dār al-Anṣār, 1977), 65.
[22] Abu al-Fatḥ Muhammad bin Abdul Karim al-Shahrastanī, nihāyat al-Iqdām fi ‘Ilm al-Kalām, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H.), 81.
[23] Fakhruddin al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, (Beirut: Dār iḥyā` al-Turāth, 1420 H.), 14:353.
[24] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422), 9:129.
[25] Abu Hasan al-Asyari, al-Luma`, 61
[26] Hamūdah Gharābah, Abu al-Ḥasan Al-Ash’ari, (Cairo: al-Hye`ah al-Āmmah li Shu`ūn al-Maṭābi’ al-Amiriyah,1973), 171.






1 komentar
Mudoffar, Thursday, 4 May 2017
Alhamdulillah niki saget membantu kulo pak